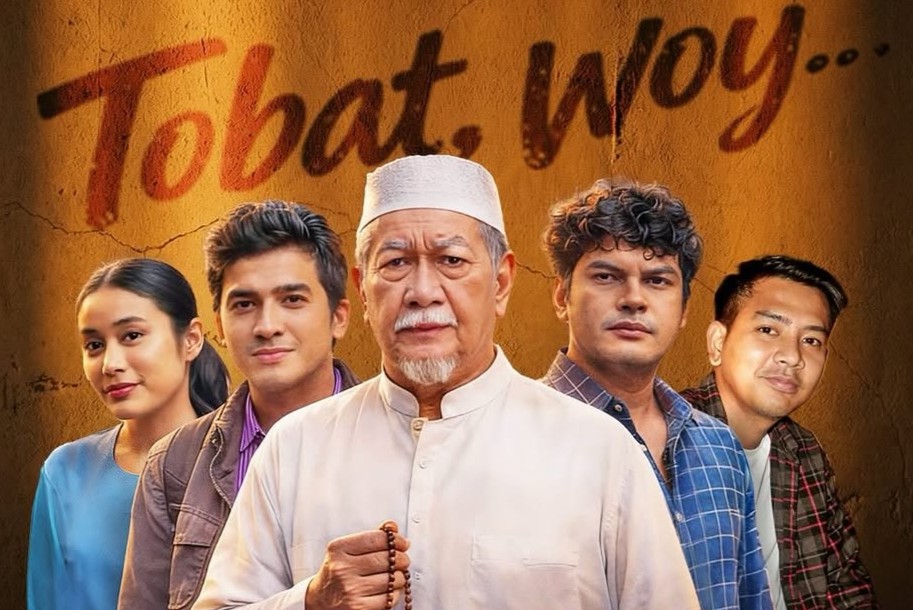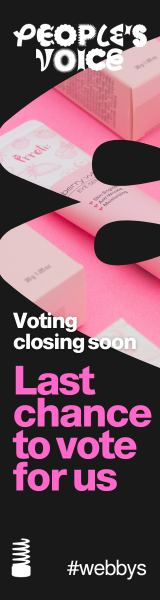Gaji Habis buat Biaya Hidup, Cerita Pekerja Jakarta Rela ‘Overwork’ demi Bertahan
Tekanan biaya hidup tinggi di Jakarta memaksa pekerja muda rela lembur dan overwork demi stabilitas penghasilan. Simak cerita Rahayu dan Mita serta dampaknya pada kesehatan mental.

SHOWBIZLINE.com – Jakarta, kota dengan segudang peluang, juga menyimpan tekanan yang tak terlihat. Di balik gemerlap gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk perkantoran, ada jutaan pekerja muda yang bergulat dengan realitas pahit, gaji habis sebelum gajian, dan lembur menjadi harga mati untuk bertahan.
Fenomena overwork atau kerja berlebihan kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan bagi banyak pekerja di Ibu Kota. Budaya kerja serba cepat, target membubung tinggi, dan biaya hidup yang terus meroket menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.
Stres berkepanjangan, burnout, hingga gangguan kesehatan mental mengintai di setiap sudut ruang kerja. Lalu, bagaimana rasanya hidup dalam tekanan ini? Dua pekerja muda Jakarta berbagi kisah mereka.
“Pulang Enggak Tentu, Revisi Beruntun Sampai Malam”
Rahayu (29), pekerja agensi kreatif di kawasan Kemang, mengawali hari bukan dengan sarapan, melainkan dengan membalas pesan klien. Secara aturan, ia masuk pukul sembilan pagi. Namun kenyataannya, pekerjaan sudah dimulai jauh sebelum ia menginjakkan kaki di kantor.
“Pulangnya juga enggak tentu, tergantung revisi atau deadline campaign. Jadi jam kerja rasanya fleksibel tapi malah panjang,” ujarnya sebagaimana dilansir dari Kompas.
Menangani beberapa klien sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Satu revisi kecil bisa memicu rangkaian pekerjaan baru hingga larut malam. Bahkan sebelum pekerjaan hari itu usai, brief baru sudah menanti esok harinya.
“Lebih ke mental sih. Harus mikir kreatif terus, tapi di saat yang sama dikejar waktu. Jadi otak rasanya enggak pernah benar-benar istirahat,” kata Rahayu.
Namun, alasan ekonomi membuatnya bertahan. Gaji di Jakarta, menurutnya, cepat habis. Stabilitas penghasilan menjadi prioritas utama di tengah tingginya biaya hidup.
“Pasti. Gaji di Jakarta kepakai cepat banget. Selama masih bisa dapat penghasilan tetap, ya dijalanin dulu walaupun capeknya lumayan,” ucap dia.
Burnout di Balik Senyuman Profesional
Pada titik tertentu, kelelahan biasa berubah menjadi burnout. Rahayu mengaku pernah mengalaminya, terutama saat beberapa kampanye besar datang bersamaan.
“Rasanya kosong saja, enggak ada semangat, bahkan hal yang dulu disukai jadi terasa berat. Tapi tetap harus kelihatan profesional di depan klien,” kenangnya.
Pola tidurnya pun berantakan. Laptop tetap menyala hingga larut, pesan klien terus dibalas, sementara waktu istirahat semakin pendek.
Lingkungan kerja sebenarnya cukup suportif, tetapi sistem industri yang bergerak cepat membuat keseimbangan hidup sulit diwujudkan.
Jika bisa mengubah sistem, ia berharap ada penghargaan nyata terhadap batas jam kerja.
“Pengin ada batas jam kerja yang benar-benar dihargai. Biar tetap produktif tanpa harus kehilangan waktu istirahat. Soalnya kerja kreatif juga butuh kepala yang sehat,” tuturnya.
Dunia Digital Tak Pernah Tidur, Pekerja pun Ikut Terjaga
Tekanan serupa dialami Mita (31), content specialist di perusahaan swasta kawasan Sudirman. Baginya, ritme industri digital yang berjalan 24 jam membuat batas waktu kerja semakin kabur.
Secara kontrak, ia bekerja delapan jam sehari. Namun praktiknya, pekerjaan sering berlanjut hingga malam untuk memantau keterlibatan audiens atau merespons tren yang berubah cepat.
“Walaupun secara kontrak delapan jam, praktiknya bisa lanjut malam buat monitor engagement atau respons tren. Dunia digital kan jalan terus, jadi rasanya ikut enggak pernah benar-benar berhenti,” ujar Mita.
Target performa menjadi tekanan utama. Konten harus ramai, relevan, dan cepat. Penurunan angka sedikit saja bisa memicu kecemasan akan penilaian kinerja.
“Kalau angka turun sedikit saja langsung kepikiran, takut dibilang enggak perform,” ungkapnya.
Kelelahan mental pun tak terhindarkan, terutama saat ide buntu tapi tenggat semakin dekat. Dampaknya merembet ke kehidupan pribadi. Bahkan saat berkumpul dengan teman, pikirannya masih tertuju pada performa konten atau analisis data.
“Lagi kumpul sama teman pun kadang masih kepikiran konten atau buka analytics. Jadi badan mungkin lagi santai, tapi pikiran tetap kerja,” tutur Mita.
Menurutnya, tekanan ekonomi di Jakarta mempersempit pilihan pekerja untuk keluar dari ritme kerja berlebih. “Biaya hidup tinggi bikin orang takut kehilangan pekerjaan. Jadi meskipun capek, tetap dipaksakan supaya terlihat tetap produktif,” jelas dia.
Psikolog: Overwork Bukan Lagi Sekadar Lelah Biasa
Ratih Ibrahim, psikolog klinis sekaligus Direktur Personal Growth, menegaskan bahwa fenomena overwork sebenarnya telah berlangsung lama. Namun kini, kesadaran pekerja akan pentingnya keseimbangan hidup justru berbenturan dengan realitas industri yang semakin mengaburkan batas kerja.
“Pekerja di masa kini semakin aware dan menuntut hak atas keseimbangan hidup untuk bisa dipenuhi. Sementara pada realitanya, kehidupan industri, bisnis, kerja secara khusus di kota besar seperti Jakarta semakin blurry batasannya,” jelas Ratih.
Bahkan, istilah work-life balance kini bergeser menjadi work-life integration, di mana aktivitas profesional, sosial, dan privat sulit dipisahkan secara tegas.
Dampak Overwork pada Kesehatan Mental
Jika dibiarkan terus-menerus, tekanan kerja tinggi bisa berdampak serius pada kesehatan mental. Mulai dari stres meningkat, kelelahan psikologis berkepanjangan, hingga burnout.
“Tingkat stres yang semakin meningkat dan intens, kelelahan psikologis yang berkepanjangan, burnout, rasa tidak berdaya, yang bisa menjadi potensi kepada rasa putus asa, depresi, dan masuk ke dalam berbagai isu mental health yang serius,” tuturnya.
Tanda-tanda burnout yang kerap muncul antara lain:
- Fisik: Lelah meski sudah istirahat, sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan, gangguan tidur, imunitas menurun.
- Mental: Kehilangan motivasi, sinis atau mudah marah, kesulitan konsentrasi, mudah lupa.
- Perilaku: Menarik diri dari lingkungan sosial, menunda pekerjaan, cuek terhadap kondisi diri sendiri.
Ratih menambahkan, banyak pekerja tetap memaksakan diri karena tuntutan ekonomi, meski kondisi mental sudah menurun. “Sangat mungkin ia jadi masa bodoh dengan kondisi dirinya, yang penting adalah tetap kerja karena memang harus bekerja,” ujarnya.
Strategi Bertahan di Tengah Tekanan
Ratih menekankan pentingnya membangun ketahanan diri atau resiliensi psikologis agar mampu menghadapi tekanan tanpa jatuh pada kelelahan berkepanjangan.
Langkah-langkah sederhana namun krusial meliputi:
- Jaga pola makan dengan asupan bergizi dan vitamin.
- Aktif bergerak dengan olahraga teratur seperti jalan pagi, jogging, atau stretching.
- Tidur cukup dan konsisten sebagai fondasi pemulihan tubuh.
- Tetapkan batas prioritas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
- Ambil cuti dan liburan sebagai kebutuhan pemulihan, bukan sekadar jeda.
“Bangun ketahanan diri, daya resiliensi dengan membangun keteraturan hidup dan disiplin. Atur makan, bergerak aktif, jaga tidur, buat batas prioritas, dan investasikan waktu untuk cuti serta liburan,” ujar Ratih.
Ia menegaskan, menjaga keseimbangan hidup bukan bentuk kemalasan, melainkan strategi mempertahankan kesehatan mental sekaligus produktivitas jangka panjang.
Di tengah kerasnya hidup Jakarta, pertanyaan besarnya bukanlah “seberapa produktif kita hari ini?”, melainkan “seberapa sehat kita bertahan?”
Kisah Rahayu dan Mita adalah cermin dari ribuan pekerja lain yang setiap hari bergulat antara tuntutan ekonomi dan hak atas hidup yang seimbang. Sudah saatnya, produktivitas tidak lagi diukur dari panjangnya jam lembur, melainkan dari kualitas hidup yang sehat dan bermakna.